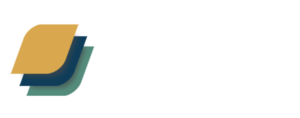Vandalisme. Ia datang dari kisah sejarah. Mula-mula ia bukanlah sebuah tindakan, melainkan nama. Konon, ia adalah nama sebuah suku di Eropa, Vandal, yang menyerbu Roma pada abad ke-5. Kota itu ditinggalkan dalam reruntuhan, tiang-tiang patah, dan dinding hangus. Sejak saat itu, setiap perusakan yang buta, setiap penjarahan yang dilakukan semena-mena, dan setiap tangan yang meruntuhkan apa yang dibangun, dilekatkan pada nama itu.
Lalu ada kata lain yang datang tidak jauh dari kita, amok. Disebutkan oleh para ahli bahasa, kata ini lahir dari bahasa Melayu. Ia menunjuk pada amarah yang tak lagi mengenal batas, semacam badai yang meledak dari dalam jiwa. Dunia Barat lalu meminjamnya menjadi idiom, running amok. Sementara kita menyimpannya dalam kata kerja sehari-hari sebagai “mengamuk”.
Dua kata itu seolah menemukan momentumnya pada sejumlah peristiwa yang hari-hari ini beritanya hadir memenuhi media massa. Demonstrasi yang mula-mula adalah pawai tuntutan politik tentang ketidakadilan menjelma menjadi arena perusakan. Pos polisi terbakar. Fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat luluh lantak. Rumah Sachroni, Eko Patrio, Uya Kuya dan Sri Mulyani dijarah. Jalan yang semula hanya dipenuhi spanduk dan orasi, mendadak menjadi panggung kobaran api dan asap. Di titik itu, protes berubah wujud, dari artikulasi politik menjadi amok, dari demonstrasi menjadi vandalisme.
Padamnya Akal
“Kemarahan adalah angin yang memadamkan pelita akal,” begitu kata seorang filsuf lebih seabad lalu. Dan kita menyaksikannya hari ini, tentang padamnya akal, dan api yang menyala. Vandalisme lalu beranak, menularkan ketakutan.
Sejarah memang menyimpan banyak momen ketika rakyat diperlakukan tidak adil, menjadikan amarah sebagai bahasa terakhir, dan mungkin kita bisa memahaminya. Tapi memahami bukan berarti membenarkan. Sebab pada saat amarah kehilangan arah, yang runtuh bukan hanya gedung dan fasilitas publik lainnya, melainkan juga makna protes itu sendiri. Tuntutan yang semula jelas tiba-tiba samar bahkan kabur ditutup debu reruntuhan dan kobaran api. Suara yang semula ingin didengar justru tenggelam di balik pekik api, perusakan dan penjarahan.
Barangkali dari sini lahirlah ironi, sesuatu yang lahir dari hasrat tidakpuasan justru menambah luka dan derita. Apa yang diniatkan sebagai teriakan keadilan berubah menjadi kabar buruk tentang kota yang porak-poranda, gedung yang dibakar dan rumah yang dijarah. Dan lagi-lagi, sejarah lama terulang, Vandal, kata yang berasal dari Eropa jauh di sana, hadir kembali di Jakarta dan kota-kota lainnya. Peradaban, ternyata mudah rapuh ketika kehilangan kendali.
“Amarah yang tak terarah adalah juga bentuk putus asa,” begitu Albert Camus mengingatkan. Ya, dalam kobaran itu, kita melihat putus asa yang meledak. Putus asa pada institusi, pada janji politik, pada kenyataan hidup sehari-hari. Tapi putus asa yang berubah menjadi amok hanya meninggalkan puing.
Menjaga Ruang Publik
Pertanyaan pun muncul, lebih penting daripada sekadar menyalahkan siapa yang memicu: bagaimana menjaga ruang publik dari amarah yang meledak? Bagaimana memastikan protes tidak kehilangan maknanya? Api bisa dipadamkan, tapi luka pada ruang bersama bisa tinggal lebih lama. Kita boleh berbeda dalam tuntutan, tapi ruang publik adalah milik bersama, dan setiap kali ia runtuh, yang kalah bukan hanya satu pihak, melainkan kita semua.
Bayangkanlah ruang publik seumpama taman. Di sana, kita menanam kepercayaan, menumbuhkan dialog, menyirami kebersamaan dengan sabar. Tetapi taman itu bisa hancur dalam satu malam bila amarah membakarnya. Yang tersisa hanya abu, dan puing. Kita bisa menanam kembali, tapi tentu saja, butuh musim-musim panjang untuk memulihkannya.
Itulah sebabnya, menjaga ruang publik dari amok dan vandalisme bukan hanya soal melindungi gedung atau fasilitas, melainkan menjaga jiwa kita sendiri. Sebab bila kita berhenti merawatnya, bila kita terbiasa melihat reruntuhan tanpa rasa kehilangan, maka sebenarnya yang runtuh bukanlah halte atau gedung publik, melainkan fondasi kebersamaan kita.
Arendt benar, kekuasaan sejati hanya ada selama kita “tetap bersama”. Dan mungkin, tugas kita hari ini adalah kembali menyalakan rasa “bersama” itu, agar rumah besar Indonesia tak retak, agar taman kita kembali tumbuh, agar setiap kota di Indonesia tidak lagi hanya menyimpan kenangan tentang amarah, melainkan juga tentang harapan yang pernah kita tanam bersama, dan kita akan menjaganya. Allahu a’lam bi-Showab.[]